Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gandhi Eka yang telah melahirkan buku komik Tamasya Purbakala (2024) yang menyenangkan untuk melihat peninggalan purbakala gua karst di Maros-Pangkep.
Buku yang mungkin akan membuka cara pandang kita soal pelestarian budaya dan arkeologi yang tadinya kita lihat hanya sebagai batu tua bergambar, tapi di balik itu ada sejarah manusia dan teknologi purba yang masih ada sampai sekarang.
Diawali dengan perjalanan seorang anak bernama Budi bersama ayahnya yang berkunjung ke museum situs arkeologi di kawasan karst Maros-Pangkep, di sana kita bisa menemukan artefak, fosil, arsip-arsip gambar purbakala, dan tentu saja gambar gua, lalu kita diajak masuk ke zaman purbakala untuk melihat makna dan bagaimana orang-orang zaman dulu bertahan hidup, bahkan bagaimana Pulau Sulawesi dan bukit karst bisa terbentuk. Semuanya dijelaskan secara imajinatif melalui kata dan gambar.
Proses bagaimana Budi tersedot ke masa lalu itu mengingatkan saya pada tayangan sinetron atau film-film yang meminjam media mesin waktu. Mungkin sepele, tapi hal tersebut penting sebagai adanya ruang untuk terlibat pengalaman langsung meski imajinatif dalam menjalani kehidupan manusia purba. Selanjutnya Budi menunggangi anoa, hewan endemik Pulau Sulawesi, dalam petualangannya.
Komik ini mengajak untuk melihat peninggalan purbakala bukan cuma benda mati, tapi catatan diam dari perjalanan manusia. Ada bukti bagaimana manusia belajar berpikir, mencipta, bertahan, dan juga asyik menjalani hari-hari dalam hidup dengan menggambar.
Saya termasuk orang yang beruntung yang bisa terlibat saat Gandhi Eka menjalani residensi di Pangkep dan bisa ikut mendampingi saat digelar lokakarya komik di sekolah dasar yang ada di Kampung Belae, kampung tempat Gandhi tinggal selama sebulan.
Mengenal Kampung Lewat Komik, itulah tema lokakarya yang digelar selama dua hari pada Rabu-Kamis, 20-21 September 2023 yang digelar di SD Negeri 49 Belae dan SD Negeri 59 Rea. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Makassar Biennale di Pangkep di tahun itu.
Ironis, beberapa murid bahkan tidak tahu keberadaan gua-gua yang ada di sekitar mereka. Jangankan mereka, saya pribadi pun masih minim pengetahuan tentang gua-gua prasejarah tersebut, apalagi tentang peninggalan purbakala. Banyak dari kita mungkin berkunjung ke Sumpang Bita, salah satu taman prasejarah yang ada di Pangkep, bukan untuk melihat sejarahnya tapi berupaya memenuhi feed Instagram dengan tangkapan kamera akan keindahan alamnya.
Beberapa dari kita, mungkin saja, senang mendaki tapi tidak semua mau meniti seribuan anak tangga hanya untuk melihat lukisan di gua tertinggi di Sumpang Bita. Informasi yang saya dengar dari Saenal, tim kerja Rumah Saraung yang aktif menemani Gandhi menelusuri gua, total ada 17 gua yang didatangi Gandhi selama menjalani residensi, termasuk meniti anak tangga yang jumlahnya seribu itu di Sumpang Bita meski tidak bisa melihat lukisan karena mulut gua dipagari dengan pintu tergembok. Memang perlu izin tertulis dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX jika ingin melakukan melihat lukisan purba.
Tamasya Purbakala, karya ini saya kira bisa menjadi refleksi untuk kita semua bahwa kita mewarisi sesuatu yang luar biasa berupa jejak pikiran manusia ribuan tahun lalu, dan warisan itu bisa hilang kalau dianggap cuma batu bukan sesuatu yang mengandung makna terkait warisan pemikiran manusia terdahulu.
Akses menuju peninggalan zaman purbakala juga tidaklah mudah. Memang benar penjagaan dan perawatan itu penting, namun akses yang mudah juga salah satu pertimbangan yang harus dipikirkan saat ingin mengajak generasi sekarang untuk itu melestarikannya.
Kebanyakan dari kita mungkin malas jika harus melalui perizinan sedemikian rupa untuk melihat peninggalan tersebut. Saat residensi pun seperti itu, untunglah juru pelihara gua di Kampung Belae ikut mendampingi sehingga lebih mudah mengakses gua prasejarah. Pak Haeruddin, juru pelihara saat itu yang kini sudah pensiun percaya jika kunjungan yang kami lakukan memanglah untuk proses belajar.
Saat membawa anak-anak sekolah dasar melihat tinggalan lukisan di gua, bisa dilihat dari ekspresi mereka bahwa itu pertama kalinya mengunjungi gua padahal letaknya hanya sekisar sepuluhan menit dari sekolah mereka. Lalu permainan tebak-tebakan pun dimulai, meski mereka asal menebak pertanyaan seputar gambar di dinding gua. Tapi saat disuruh menirukan gambar tersebut bisa saya lihat mereka mengamati, mereka mencari gambar apa lagi yang bisa ditemukan di gua itu. Ada rasa penasaran menemukan gambar apa lagi yang ada. Ada pertanyaan di kepala mereka, mengapa cuma gambar itu dan tidak ada gambar ini.
Kunjungan langsung tersebut bagian dari lokakarya komik, Gandhi hendak memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak agar terdorong menggambar komik dan karya mereka ikut dipajang dalam pameran. Kompilasi karya komik mereka pun dibukukan oleh Gandhi dan dibagikan kepada semua anak-anak di pembukaan pameran pada tahun 2023 lalu.
Setelah sekian lama, mungkin sudah satu tahunan setelah saya menerima komik ini, saya kembali diajak oleh Rumah Saraung untuk membincangnya. Kali ini Tamasya Purbakala hadir di tengah kerumunan pegiat komunitas di Pangkep. Saya membayangkan bagaimana tinggalan masa lalu akan terus diperbincangkan jika masih ada yang peduli. Sore itu, Minggu 3 Agustus 2025 saya agak grogi mengutarakan pendapat saya atas komik ini. Namun semuanya berlalu juga karena rupanya komik ini ditanggapi dengan antusias oleh teman-teman komunitas.
Komik ini rupanya telah berjalan jauh mengisi rak-rak baca komunitas dan sekolah-sekolah di Pangkep. Hal itu saya dengar dari penuturan Muh Ardi Sangkala dari Pelita Pangkep, komunitas yang fokus pada literasi anak di Pangkep, melalui sejumlah programnya ia membawa komik ini menjumpai pembacanya lebih luas.
Sampai di sini, saya ingin katakan kalau karya ini mengingatkan bahwa literasi itu bukan cuma soal membaca kata, tapi membaca dunia, termasuk dunia di masa lalu. Dan, dari komik ini kita juga diingatkan bagaiamana menjaga alam. Banyak hal yang kita sebut “kemajuan”, tapi alam menyebutnya “luka”.
Karya ini sesederhana bentuknya, namun memberi kita kesempatan untuk membaca masa lalu dengan kesadaran masa kini untuk mendorong adanya tindakan kecil untuk lebih menghargai dan mencintai alam. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun masa depan hingga lupa memelihara jejak langkah sendiri. Jangan sampai kita punya banyak kata tapi kehilangan makna.
:: Siti Husnul Zakiyah, penyiar radio. Kontributor Hanya Ada Babak, Tidak Ada Panggung (2024).
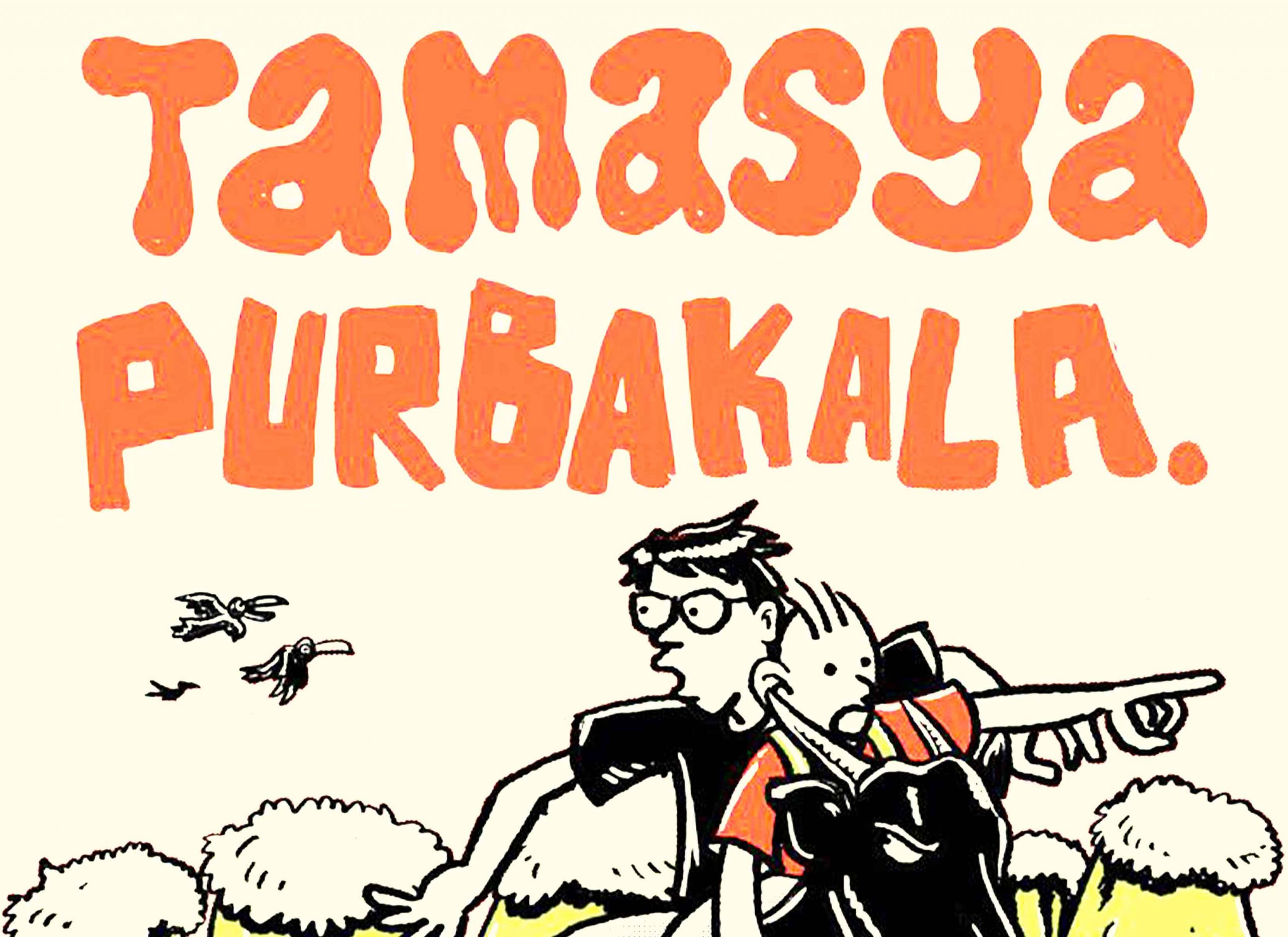
Tinggalkan Balasan